Di Indonesia, sekolah dan kampus masih dianggap jalur paling aman untuk memperbaiki nasib. Orang tua bekerja keras agar anak bisa kuliah, dengan harapan gelar sarjana akan membuka pintu ke pekerjaan yang stabil. Tapi data terbaru justru memberi sinyal berbeda jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur terus bertambah, seolah ijazah tidak lagi otomatis berarti pekerjaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 di kisaran 4,76 persen. Dari total sekitar 7,28 juta orang pengangguran, lebih dari 1 juta di antaranya lulusan diploma dan sarjana. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya, dari 5,25 persen menjadi 6,23 persen di kelompok pendidikan tinggi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan tinggi di Indonesia benar-benar selaras dengan dunia kerja?
Salah satu masalah utamanya adalah ketidakseimbangan antara output kampus dan kebutuhan industri. Kampus setiap tahun meluluskan ribuan sarjana dari jurusan yang sama, tapi industri tidak mampu menampung semuanya. Misalnya, bidang administrasi, hukum, dan ilmu sosial populer di kampus-kampus besar, tapi lapangan kerja yang relevan terbatas. Akhirnya lulusan bersaing ketat untuk posisi yang jumlahnya sedikit.
Di sisi lain, industri juga mengeluhkan soal keterampilan praktis. Banyak lulusan yang paham teori tapi tidak terbiasa dengan situasi kerja nyata. Soft skill seperti komunikasi, kemampuan kerja tim, dan adaptasi teknologi masih lemah. Padahal, perusahaan lebih suka tenaga kerja yang bisa langsung produktif, bukan yang masih perlu dilatih dari nol.
Kesenjangan ini makin terasa ketika ekonomi global sedang melambat. Perusahaan di berbagai sektor cenderung menahan ekspansi, sehingga lowongan kerja baru tidak sebanyak tahun-tahun lalu. Sektor manufaktur, yang biasanya jadi penyerap besar tenaga kerja, tertekan oleh biaya produksi dan persaingan impor. Otomatisasi juga menggantikan sebagian pekerjaan yang dulunya dikerjakan tenaga manusia. Jadi, walau jumlah lulusan meningkat, daya serap pasar tenaga kerja tidak ikut naik.
Gelar Masih Dianggap sebagai Simbol Status Semata
Penting dicatat, masalah ini tidak hanya soal kampus, tapi juga pola pikir masyarakat. Gelar masih sering dianggap simbol status, bukan sebagai bagian dari strategi karier yang realistis. Banyak orang tua mendorong anak kuliah di jurusan “bergengsi” tanpa mempertimbangkan prospek kerja. Tidak heran jika kemudian jumlah sarjana melimpah, tapi bidang kerja yang mereka incar sebenarnya sudah penuh.
Di sisi lain, jurusan yang sebenarnya dibutuhkan industri, seperti teknologi informasi, pertanian modern, atau teknik terapan, justru sering kekurangan peminat. Ini menciptakan paradoks, ada lapangan kerja terbuka di sektor tertentu, tapi tidak ada cukup lulusan yang siap mengisinya.
Pemerintah memang mencoba menjembatani kesenjangan ini dengan program link and match, sertifikasi, dan magang berskala nasional. Kampus juga didorong menyiapkan kurikulum Merdeka Belajar yang lebih fleksibel. Namun di lapangan, akses program seperti ini masih timpang. Kampus besar di kota-kota besar lebih mudah terkoneksi dengan industri, sedangkan kampus di daerah sering kesulitan. Akibatnya, peluang mahasiswa untuk mendapat pengalaman praktis berbeda jauh tergantung lokasi kampusnya.
Selain itu, tidak semua perusahaan mau terlibat serius dalam pendidikan. Ada yang hanya menerima magang sebagai formalitas, tanpa memberi pengalaman nyata. Jika praktik seperti ini berlanjut, link and match hanya akan jadi jargon tanpa hasil.
Fenomena sarjana menganggur membawa dampak sosial yang besar. Anak muda yang sudah menginvestasikan waktu dan biaya pendidikan tinggi bisa kehilangan motivasi ketika realitas tidak sesuai harapan. Rasa frustrasi mudah muncul, apalagi ketika melihat bahwa pekerjaan yang tersedia kadang justru diisi oleh lulusan dengan pendidikan lebih rendah.
Masyarakat juga perlahan mempertanyakan: untuk apa biaya kuliah yang mahal kalau akhirnya tidak ada jaminan pekerjaan? Pertanyaan ini berpotensi menggerus kepercayaan terhadap sistem pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi.
Ke depan, kunci penyelesaian ada pada dua hal. Pertama, penyesuaian skala besar antara kebutuhan tenaga kerja dan arah pendidikan tinggi. Kampus perlu jujur melihat data pasar kerja sebelum membuka atau memperluas jurusan. Kedua, fokus pada pengembangan keterampilan nyata, baik teknis maupun nonteknis. Lulusan yang hanya membawa gelar tanpa keterampilan tidak akan kompetitif di pasar kerja.
Gelar masih penting, tapi nilainya akan turun jika tidak diikuti kompetensi. Dunia kerja sekarang menilai kemampuan lebih dari sekadar ija...

 3 hours ago
1
3 hours ago
1








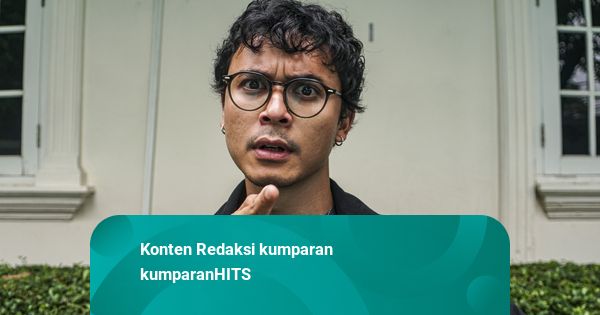











:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4974046/original/094131900_1729434804-lionel_messi_Inter_Miami_Juara-3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5291812/original/090583100_1753197347-tha.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5316351/original/043054100_1755233091-1.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4664154/original/030267800_1701052268-20231127-Juventus-Vs-Inter-Milan-AFP-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5296951/original/071845600_1753642748-AP25208679077050.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5296285/original/089001500_1753547737-IMG-20250726-WA0104.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1547839/original/083660200_1490556850-Espai_Barca.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5293124/original/032456200_1753306384-AP25204773803880.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295323/original/095723000_1753434107-IMG_3889.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5065921/original/032477700_1735175743-pep-guardiola_f1802d7.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5293334/original/023724100_1753327430-AP25203754414037.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5297112/original/007230400_1753672392-chloe_kelly_timnas_inggris_euro_2025_wanita.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5296196/original/094112400_1753529041-90947aa6-ba73-45f1-827a-b0c654fc9249.jpeg)
